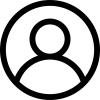Oleh: Nany Afrida
INDEPENDEN --Di Papua, hutan bukan sekadar bentang alam hijau di peta pembangunan. Ia adalah rumah, lumbung pangan, ruang spiritual, dan penanda identitas. Ketika hutan itu terancam, yang dipertaruhkan bukan hanya lingkungan, tetapi keberlanjutan hidup sebuah masyarakat.
Namun dalam narasi pembangunan nasional, suara-suara yang datang dari tanah Papua sering kali dibingkai sebagai gangguan—bahkan ancaman—terhadap kemajuan.
Riset Asia Centre tentang Climate Disinformation in Indonesia menunjukkan bagaimana kritik terhadap proyek pembangunan dan kebijakan iklim kerap dipelintir. Di Papua, pembingkaian itu terasa paling telanjang: ketika masyarakat adat mempertanyakan dampak pembangunan, mereka dicap menghambat kemajuan.
Bagi masyarakat adat Papua, tanah tidak bisa dipisahkan dari manusia. Tanah adalah leluhur, sejarah, dan masa depan. Ketika proyek-proyek besar masuk—perkebunan skala luas, tambang, infrastruktur—tanah sering kali direduksi menjadi aset ekonomi. Di titik inilah benturan terjadi.
Asia Centre mencatat bahwa kritik masyarakat adat Papua jarang dipahami sebagai ekspresi hak, melainkan sebagai penolakan terhadap agenda negara. Narasi pembangunan memosisikan Papua sebagai wilayah yang “harus dikejar kemajuannya”, sementara masyarakat adat dianggap tertinggal dan perlu “dibawa masuk” ke arus modernisasi.
Padahal, yang sering terjadi adalah pengambilan keputusan tanpa persetujuan yang bermakna.

Tiga Temuan
Di Indonesia, masyarakat adat diperkirakan mencakup 18 hingga 26 persen dari total penduduk, atau sekitar 50 hingga 70 juta jiwa dari 284,5 juta penduduk Indonesia Data ini berasal dari International Work Group for Indigenous Affairs/IWGIA tahun 2025, juga Badan Pusat Statistik tahun 2025.
Meski jumlahnya signifikan, masyarakat adat justru menghadapi kerentanan struktural yang semakin dalam. Hal ini terjadi seiring prioritas pemerintah pada agenda pembangunan nasional yang kerap mengesampingkan perlindungan hak, pengakuan wilayah adat, serta dampak sosial dan lingkungan yang harus ditanggung komunitas adat. Akibatnya, kelompok yang seharusnya menjadi bagian penting dari masa depan Indonesia justru terus berada di posisi paling rentan dalam arus pembangunan.
Tanah Papua, yang kini mencakup enam provinsi—Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya—merupakan wilayah dengan tingkat keragaman etnis tertinggi di Indonesia.
Menurut data IWGIA lagi, kawasan Papua ini menjadi rumah bagi lebih dari 250 bahasa adat, dengan lebih dari separuh penduduknya berasal dari kelompok Melanesia asli.
Kekayaan budaya dan bahasa tersebut menempatkan Papua sebagai wilayah yang sangat penting, tidak hanya secara ekologis, tetapi juga sebagai pusat keberagaman masyarakat adat di Indonesia. Namun, di tengah ekspansi pembangunan dan proyek-proyek berskala besar, keragaman ini menghadapi tekanan serius, terutama ketika kebijakan nasional tidak sepenuhnya mempertimbangkan hak, pengetahuan, dan cara hidup masyarakat adat Papua.
Kartini Sunityo, Partnership Manager di Asia Centre, pada akhir Januari 2026 lalu memaparkan temuan kunci dari draf laporan Indonesia https://asiacentre.org/climate-disinformation-in-indonesia-prioritising-development-over-indigenous-peoples-vulnerability/ dengan menyoroti tiga persoalan yang saling terkait dan membentuk situasi masyarakat adat di Indonesia saat ini, termasuk Papua.
Pertama, ia menekankan posisi resmi negara yang tidak mengakui masyarakat adat sebagai pemegang hak yang berbeda dan khusus. Pendekatan ini menyimpang dari kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengakui hak kolektif masyarakat adat. Dengan memperlakukan semua warga negara sebagai “sama”, negara justru menghapus realitas ketimpangan historis dan kebutuhan perlindungan khusus bagi masyarakat adat.
Kedua, rencana pembangunan nasional masih menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas utama, sambil mengabaikan biaya sosial, lingkungan, dan pelanggaran hak yang harus ditanggung masyarakat adat. Dampak-dampak ini sering dianggap sebagai konsekuensi yang tak terelakkan—bukan sebagai masalah serius yang menuntut pertanggungjawaban.
Ketiga—dan yang paling krusial—Kartini menjelaskan bahwa disinformasi iklim memperkuat kedua persoalan tersebut.
Melalui narasi yang menyederhanakan pembangunan sebagai sesuatu yang selalu membawa kebaikan, disinformasi iklim menutupi dampak buruk proyek-proyek pembangunan. Dalam narasi ini, klaim dan kritik masyarakat adat diposisikan sebagai penghambat kemajuan, bukan sebagai peringatan atau masukan berbasis pengalaman hidup.
“Ketika pembangunan selalu digambarkan sebagai solusi, suara masyarakat adat justru dipinggirkan,” tegas Kartini.
Dampaknya, ruang dialog menyempit, kritik kehilangan legitimasi, dan ketidakadilan terhadap masyarakat adat terus direproduksi—kali ini dengan bungkus kebijakan iklim dan pembangunan.
Paparan ini menegaskan satu hal penting: masalahnya bukan semata pada pembangunan, melainkan pada cara narasi dibangun dan siapa yang diizinkan untuk bersuara di dalamnya.
Mengaburkan dampak
Disinformasi iklim di Papua tidak selalu berupa informasi palsu. Ia bekerja lewat pengaburan dampak.
Proyek disebut membawa lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan. Yang jarang dibicarakan adalah perubahan drastis dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat.
Hutan yang dibuka berarti jalur berburu hilang. Sungai yang tercemar berarti ikan berkurang. Perempuan harus berjalan lebih jauh untuk mendapatkan air bersih.
Namun pengalaman ini jarang masuk ke narasi besar pembangunan. Kritik yang disampaikan masyarakat adat terhadap dampak tersebut kerap disederhanakan menjadi sikap emosional atau ketakutan akan perubahan.
Asia Centre menyoroti bahwa narasi ‘demi kemajuan’ sering digunakan untuk menutup ruang diskusi. Dengan cara ini, kritik kehilangan legitimasi, sementara proyek terus berjalan.
Pembingkaian kritik sebagai penghambat kemajuan tidak berhenti di level wacana. Di Papua, hal ini sering berlanjut menjadi tekanan nyata. Masyarakat adat yang bersuara menghadapi stigma, intimidasi, bahkan kriminalisasi.
Sandra Winarsa, Climate and Energy Advisor di Humanis Foundation, menegaskan bahwa disinformasi iklim di Indonesia bukanlah sesuatu yang terjadi secara tidak sengaja. Menurutnya, disinformasi tersebut bersifat disengaja, politis, dan struktural.
Ia menjelaskan bahwa banyak proyek pembangunan kerap “dipresentasikan seolah-olah peduli”, padahal di balik narasi itu tersembunyi dampak sosial dan lingkungan yang serius.
Sandra menyoroti proyek-proyek yang dilabeli “hijau”, seperti panas bumi dan energi terbarukan, yang sering dijalankan secara top-down, tidak peka gender, dan terburu-buru. Akibatnya, ketika proyek-proyek tersebut bermasalah, masyarakat lokal justru disalahkan, alih-alih desain kebijakan dan proses pengambilan keputusan yang cacat.
“Proyek-proyek ini sering mengabaikan suara komunitas sejak awal, tetapi ketika gagal, komunitaslah yang dituding sebagai penghambat,” ujarnya.
Pandangan tersebut diperkuat oleh Haeril Halim, Media Manager Amnesty International Indonesia, yang menyoroti kriminalisasi masyarakat adat dan peran disinformasi dalam memperparah situasi tersebut.
Ia menyebut laporan ini menjadi sangat relevan di tengah banjir mematikan, meningkatnya serangan terhadap pembela HAM, serta ancaman yang kian besar terhadap masyarakat adat.
Haeril menjelaskan bahwa disinformasi yang diproduksi atau direproduksi oleh negara kerap melabeli LSM dan aktivis sebagai agen asing atau anti-pembangunan, sehingga melemahkan kampanye hak asasi manusia. Situasi ini diperparah oleh liputan media yang sering tidak berimbang—memberitakan penangkapan tanpa menghadirkan perspektif masyarakat sipil.
“Akibatnya, publik bisa dengan mudah disesatkan untuk melihat pembelaan lingkungan dan hak adat sebagai tindakan kriminal,” kata Haeril.
Asia Centre mencatat bahwa disinformasi iklim berfungsi sebagai pembenaran sosial atas tindakan represif. Ketika kritik dianggap mengganggu stabilitas dan pembangunan, maka tindakan keras dapat dibingkai sebagai upaya menjaga ketertiban.
Bagi masyarakat adat Papua, ini berarti ruang aman untuk berbicara semakin sempit.
Ironisnya, masyarakat adat Papua memiliki pengetahuan ekologis yang sangat relevan dalam menghadapi krisis iklim. Mereka memahami tanda-tanda perubahan cuaca, pergeseran musim, dan keseimbangan hutan berdasarkan pengalaman lintas generasi.
Namun pengetahuan ini jarang diakui dalam kebijakan.
Temuan Asia Centre menegaskan bahwa pengetahuan adat sering dianggap kalah valid dibanding kajian teknis. Ketika masyarakat adat berbicara dari pengalaman, suara itu dipinggirkan karena tidak sesuai dengan bahasa pembangunan yang dominan.

Perempuan Adat: Suara yang Paling Sunyi
Perempuan adat di Papua berada di garis depan dampak perubahan lingkungan. Mereka bertanggung jawab atas pangan, air, dan kesehatan keluarga. Ketika hutan rusak, merekalah yang pertama merasakan konsekuensinya.
Namun suara perempuan adat sering kali paling jarang didengar.
Asia Centre juga mencatat bahwa disinformasi iklim juga memperkuat ketimpangan gender. Kritik perempuan adat sering dianggap emosional atau tidak relevan, padahal justru berangkat dari pengalaman paling nyata.
Devi Anggraini, Ketua PEREMPUAN AMAN (Perkumpulan Perempuan Adat Nusantara), menegaskan bahwa pengakuan negara terhadap hak-hak masyarakat adat di Indonesia masih terpecah-pecah dan tidak terkoordinasi antar-kementerian.
Kondisi ini membuat perlindungan terhadap masyarakat adat—terutama perempuan adat—menjadi lemah dan tidak konsisten.
Ia menyoroti bahwa sejumlah regulasi penting, termasuk Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat, hingga kini belum diimplementasikan secara menyeluruh, sehingga hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam masyarakat adat tetap berada dalam posisi rentan.
Devi juga menggarisbawahi tantangan tambahan yang dihadapi perempuan adat, bukan hanya disinformasi iklim, mereka juga harus menghadapi proyek-proyek energi hijau yang dijalankan tanpa konsultasi bermakna, hingga hambatan bahasa. Faktor-faktor ini kerap membuat perempuan adat tidak memahami—atau tidak dilibatkan sama sekali—dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada tanah dan ruang hidup mereka.
“Ketika informasi tidak sampai, atau disampaikan dengan bahasa yang tidak kami pahami, perempuan adat otomatis tersingkir dari proses pengambilan keputusan,” ujarnya.
Pernyataan Devi mempertegas bahwa krisis iklim dan transisi energi tidak netral gender. Tanpa pengakuan hukum yang utuh dan komunikasi yang inklusif, kebijakan yang diklaim berkelanjutan justru berisiko memperdalam ketimpangan dan menyingkirkan perempuan adat dari hak atas masa depan mereka sendiri.
Di Papua, pertanyaan tentang kemajuan selalu berujung pada satu persoalan mendasar: siapa yang menentukan arah, dan siapa yang menanggung akibatnya.
Ketika kritik terus dipelintir sebagai hambatan, yang hilang adalah kesempatan untuk memperbaiki arah pembangunan sebelum terlambat.
Disinformasi iklim telah mengubah penjaga hutan menjadi penghalang, dan peringatan dini menjadi gangguan. Padahal, masyarakat adat Papua tidak menolak masa depan. Mereka menolak kehilangan tanah, hutan, dan kehidupan yang menjadi dasar keberadaan mereka.
Papua adalah salah satu wilayah dengan cadangan hutan tropis terbesar di Indonesia, sekaligus rumah bagi banyak komunitas adat dengan ketergantungan kuat pada hutan sebagai sumber pangan, budaya, dan identitas. Namun berbagai data menunjukkan bahwa lingkungan ini sedang dalam tekanan besar.
Menurut analisis data Global Forest Change, Papua telah mengalami deforestasi tahunan yang signifikan, terutama akibat perluasan lahan untuk perkebunan skala besar dan aktivitas komersial lainnya. Data tersebut menunjukkan tren penurunan luas hutan alam yang mengkhawatirkan sepanjang dekade terakhir.
Laporan lain menyebutkan bahwa dalam rentang 2001–2021, Provinsi Papua kehilangan sekitar 2% dari hutan alaminya, setara dengan lebih dari 748.000 hektar. Mengingat hutan Papua memiliki peran besar dalam menyerap karbon dan menjaga keseimbangan iklim lokal, kehilangan ini merupakan indikator jelas tentang tekanan terhadap ekosistem dan kerentanan masyarakat adat yang hidup di dalamnya.
Dan saat ini, wilayah Papua menjadi fokus ambisi pembangunan nasional dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Media internasional melaporkan bahwa pemerintah Indonesia sedang menggalakkan proyek pertanian skala besar, termasuk budidaya tebu dan padi di sekitar 3 juta hektar hutan Papua, termasuk penyiapan infrastruktur pendukung seperti jalan, pelabuhan, dan bandara.
Proyek ini kerap dipromosikan sebagai bagian dari strategi food security dan penyediaan energi berbasis bioetanol, agenda yang diklaim dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat lokal.
Namun bagi warga adat Papua, proyek tersebut dipandang sebagai ancaman besar terhadap hutan, sumber mata pencaharian, dan sistem pengetahuan tradisional yang berakar kuat pada keseimbangan alam.