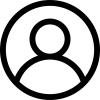Oleh : Novriani Tambunan, Indah Cahyani, Alberto Nainggolan
INDEPENDEN— “Kau rezekiku, aku mau cari rezeki. Tolong kerja sama denganku agar keluargaku bisa hidup.” Pak Tiara berucap untuk merayu pohon aren.
Setiap pagi sebelum memulai kegiatan, lelaki berusia 46 tahun itu memiliki ritus yang diwariskan turun-temurun: mangelek.
Artinya, membujuk pohon aren dengan kalimat sederhana namun penuh harap.
Rutinitas hariannya dimulai dengan marragat—menyadap nira dari pohon aren—yang dilakukan dua kali sehari, pagi dan sore. Proses ini melibatkan penyayatan halus pada bagian tandan bunga jantan (mayang) agar air nira dapat mengalir dan ditampung di dalam wadah bambu atau plastik.
Penyadapan tidak bisa tergesa-gesa; butuh ketelatenan dan rasa.
Jika terlalu dalam menyayat dapat merusak pohon, sementara bila dangkal hasil yang keluar tak maksimal.
Yang dipotong dari pohon adalah tangkainya atau disebut tangki bunga jantan.
Itulah yang dideres.
Bagi seorang paragat, pohon aren bukan sekadar objek produksi melainkan makhluk hidup yang memiliki jiwa.
Ada ikatan emosional yang terbangun dari kebiasaan harian, seolah terjalin hubungan batin antara penyadap dan pohon yang dirawatnya.
“Rasanya seperti terkoneksi. Seperti seorang laki-laki yang sedang merayu perempuan,” tuturnya.
Perumpamaan itu tak berlebihan.
Setiap hari dia mendekati pohon dengan kelembutan dan kesabaran—memilih waktu yang tepat, menyentuh dengan hati-hati, dan menyayat dengan perasaan.
Tak bisa dipaksa, karena jika terlalu tergesa pohon dapat ‘tersinggung’ sehingga ogah mengeluarkan air.
Dalam hubungan itu ada rasa saling percaya yang tumbuh pelan-pelan hingga pohon memberikan hasil terbaiknya. Sebelum memanjat pohon dan memulai penyadapan, Pak Tiara senantiasa menyempatkan diri untuk berdoa. Terlebih ketika pertama kali sebuah pohon mulai disadap.
Ada sebuah tradisi yang disebut tuak pamuang—yakni mengadakan makan bersama seperti memotong ayam di lapo [lepau] sebagai bentuk syukur dan permohonan agar pohon tersebut subur dan menghasilkan tuak dengan lancar.

Membangun Rumah
Dalam satu hari Pak Tiara bisa memanen hingga tiga kaleng tuak.
Satu kaleng berisi 10 teko, dan setiap teko dijual Rp11.000. Artinya, dalam sehari ia bisa berpenghasilan sekitar Rp330.000. Jumlah yang cukup stabil dan layak, terutama di daerah seperti Sionggang, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara.
Ia mulai berjualan sekitar pukul lima sore dan tutup antara pukul sebelas malam hingga dini hari meskipun ada pula pelanggan yang betah minum hingga subuh.
Di laponya sendiri ia mematok harga Rp3.500 per cangkir.
Tak hanya untuk konsumsi lapo di sekitar kampung, tuaknya.
Dia juga memiliki beberapa agen tetap yang datang mengambil minuman beralkohol itu untuk dijual kembali ke berbagai tempat lain.
Setiap sore, para reseller akan datang menjemput hasil sadapan.
Jaringan distribusi ini membuat tuaknya dikenal luas.
Tidak hanya dinikmati oleh warga sekitar Sionggang, tetapi juga sampai ke Panei Tongah dan Bah Jambi.
Hal ini secara tidak langsung membantu memperkenalkan kualitas tuak dari Sionggang ke lebih banyak orang.
Ia pun merasa bangga karena hasil kerjanya bisa turut menjaga keberlanjutan tradisi sekaligus menopang kehidupan banyak orang lainnya.
Bagi para paragat seperti Tiara yang tidak memiliki lahan atau pohon aren sendiri, sistem kerja yang umum digunakan adalah bagi hasil.
Setiap minggu, hasil penjualan tuak dibagi sesuai kesepakatan antara pemilik pohon dan Tiara.
Sistem ini memungkinkan kerja sama yang saling menguntungkan: paragat bisa terus menjalankan aktivitas produksinya tanpa harus memiliki aset tanah, sementara pemilik pohon tetap mendapatkan pemasukan dari pohon miliknya.
Pola kerja seperti ini sudah berlangsung lama dan menjadi bagian dari ekonomi lokal yang berbasis pada kepercayaan dan relasi sosial di tingkat komunitas.
Lalu, apakah pekerjaan sebagai paragat menjanjikan secara ekonomi? Dengan mantap ia menjawab, “Benar, penghasilanku dari tuak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.”
Penghasilan ini memberinya kestabilan ekonomi tanpa harus merantau jauh dari kampung halaman.
“Dari tuak ini, aku bisa bangun rumah dan sekolahkan anak-anak,” ungkapnya dengan bangga.
Kalimat sederhana itu merangkum perjalanan panjang seorang pekerja lokal yang menggantungkan harapannya pada pohon-pohon aren yang setia memberi rezeki.
Hasil kerja sebagai paragat selama bertahun-tahun telah memberikan dampak nyata bagi kehidupan Pak Tiara dan keluarganya.
Dari penghasilan yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit ia berhasil membangun rumah sendiri—sebuah pencapaian yang lahir dari ketekunan dan kesabaran dalam menjalani profesi tradisional ini.
Tak hanya itu, pekerjaan sebagai penyadap tuak juga memberinya kemampuan untuk membiayai pendidikan anak-anaknya.
Baginya, menyekolahkan anak adalah bentuk investasi masa depan dan bukti bahwa maragat, meski sering dipandang sebelah mata, tetap memiliki daya hidup yang kuat jika dikelola dengan tekun.
Selain itu, dengan tetap tinggal di tanah kelahiran ia bisa menjalani hidup sederhana namun layak sambil terus melestarikan tradisi turun-temurun sebagai penderes tuak.
Ketika ditanya soal tips atau trik agar produksi tuaknya banyak dan lancar, ia menjawab dengan rendah hati, “Aku cuma bisa membujuk Tuhan.”
Ungkapan ini bukan sekadar candaan tapi menunjukkan keyakinannya bahwa hasil terbaik berasal dari restu Yang Maha Kuasa.

Keahlian Khusus
Pria kelahiran 1982 ini telah 26 tahun menekuni pekerjaannya sebagai paragat atau penderes tuak dan hingga kini tetap setia menggantungkan hidup dari air nira yang diturunkan langsung dari pucuk-pucuk pohon aren untuk menghidupi keluarga.
Bagi sebagian orang, menjadi paragat mungkin pilihan karena keterpaksaan.
Namun bagi pria ini, jalan hidup sebagai penyadap tuak adalah warisan yang sudah tertanam sejak ia dilahirkan.
“Orang tuaku dulu juga paragat,” katanya. “Jadi bisa dibilang, ilmuku soal tuak itu sudah dari lahir.”
Meski telah akrab dengan dunia tuak sejak kecil, ia baru benar-benar menekuni pekerjaan ini secara penuh waktu pada usia 26 tahun.
Keputusan itu bukan semata mengikuti jejak orang tua melainkan juga karena keterampilan yang dimilikinya memang mengarah ke sana.
“Nggak semua orang yang punya tanah dan pohon tuak bisa langsung maragat,” jelasnya. “Ini bukan cuma soal keberanian naik pohon, tapi ada teknik dan rasa yang harus dilatih.”
Menyadap tuak memang membutuhkan keahlian khusus—dari mengenali kapan waktu terbaik untuk meragat, bagaimana menyayat mayang agar tak rusak, hingga menjaga kebersihan dan keaslian nira.
“Kualitas tuak itu juga sangat tergantung pada paragatnya,” ujar Pak Tiara.
Teknik menyayat, waktu penyadapan, hingga cara merawat alat dan wadah penyimpanan, semuanya memengaruhi hasil akhir.
Ada tips penting dalam menjaga kualitas dan masa ketahanan tuak yaitu dengan memperhatikan kebersihan wadah penyimpanan.
Jerigen atau tempat penampung nira harus dalam kondisi benar-benar bersih agar tuak tidak cepat mengalami fermentasi berlebihan yang menyebabkan rasa menjadi terlalu asam atau bahkan basi.
“Kuncinya di kebersihan,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa kelalaian sekecil apa saja dalam hal sanitasi dapat memengaruhi cita rasa tuak secara drastis.
Oleh karena itu, setiap paragat atau pelaku usaha tuak disarankan untuk selalu mencuci dan mengeringkan wadah sebelum digunakan, serta tidak mencampur tuak baru dengan sisa lama yang sudah mulai asam.
Dengan perawatan yang tepat kualitas tuak bisa terjaga lebih lama dan tetap layak dikonsumsi dalam kondisi segar.
Menariknya lagi, meskipun dua paragat menyadap dari pohon-pohon yang tumbuh di lahan yang sama, tuak yang mereka peroleh belum tentu memiliki kualitas yang serupa.
Perbedaan itu bukan karena kondisi tanah atau pohonnya semata melainkan karena tangan yang mengolahnya.
Hal ini menunjukkan bahwa menjadi maragat bukan sekadar soal memanjat dan menyadap melainkan seni yang menggabungkan pengalaman, ketelatenan, dan rasa tanggung jawab terhadap kualitas.
Tuak yang baik tidak hanya dihasilkan dari pohon yang sehat tetapi juga oleh tangan yang piawai dan hati yang tulus dalam bekerja.
Ia pun mengakui dengan jujur, “Aku juga memutuskan jadi paragat karena enggak punya skill lain, he..he..he…” candanya, diselingi tawa ringan yang menandakan penerimaan sepenuhnya terhadap pekerjaan yang kini menjadi tumpuan hidup.
Ia memandang pohon aren bukan sekadar sumber nira, melainkan ladang rezeki yang harus dijaga dan dihormati.

Gaya Hidup
Ajis, 34 tahun, merupakan salah satu pelanggan setia yang mengenal tuak sejak usia 21. Baginya, tuak bukan sekadar minuman tapi bagian dari gaya hidup yang terhubung dengan akar budaya Batak. “Tuak ini alami, beda dengan alkohol pabrikan,” katanya.
Ia melihat lapo tuak sebagai ruang sosial yang inklusif—tempat segala hal bisa diperbincangkan, mulai dari urusan bisnis, politik lokal, hingga persoalan pendidikan.
Fungsi lapo melampaui sekadar tempat berkumpul; ia menjadi forum publik informal yang mempertahankan nilai-nilai keterbukaan, gotong royong, dan relasi antargenerasi.
Menurut Ajis, keaslian lapo tradisional dengan bangunan sederhana masih sulit tergantikan. “Tak salah mengikuti zaman, tapi suasana lapo yang kayak begini lebih tenang dan akrab dibanding yang sudah mirip kafe dengan karaoke.”
Baginya, lapo bukan soal fasilitas, tetapi soal rasa dan ikatan—pengalaman sosial yang tulus, dan jauh dari hiruk-pikuk hiburan artifisial.
Perubahan gaya lapo dengan fasilitas modern seperti karaoke memang menunjukkan adanya dinamika konsumsi.
Namun, pelanggan seperti Ajis tetap mencari pengalaman yang lebih otentik—tempat di mana obrolan mengalir tanpa polesan, dan tuak dinikmati sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari yang penuh makna.
Praktik menikmati tuak dalam balutan gaya modern pertama kali dicetuskan oleh dua anak muda kreatif, Indra Sihotang dan Benny Purba.
Bukan orang baru dalam dunia per-tuak-an, sebelumnya mereka telah sukses menginisiasi sebuah festival tuak yang menarik perhatian publik.
Dari pengalaman itu lahirlah gagasan untuk menghadirkan ruang baru—sebuah tempat yang tidak hanya menyajikan tuak, tetapi juga mempertemukan budaya, kreativitas, dan suasana kekinian.
Tempat berkonsep alam ini dalam penggodokan idenya melibatkan musisi asal Siantar, Diknal Sitorus, dan tokoh komunitas kreatif setempat, Tumpak Winmark ‘Siparjalang’ Hutabarat.
Kedua orang ini melihat tuak bukan sekadar sebagai minuman tradisional melainkan juga simbol budaya yang bisa dirayakan dalam suasana yang lebih inklusif dan terbuka, khususnya bagi masyarakat di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun.
Dari semangat itulah Lissoii—sebuah kafe di kota Pematangsiantar yang bisa dikatakan sebagai pelopor dalam menjadikan tuak sebagai ikon utama—lahir.
Tidak hanya sebagai menu suguhan tetapi juga sebagai identitas.
Sang pemilik sendiri yang dikenal memiliki kecintaan terhadap tuak memutuskan untuk mewujudkan mimpi ini dalam bentuk nyata yaitu sebuah kafe tuak yang memadukan tradisi dan gaya hidup urban.
Kafe ini mulai berdiri sejak 2020. Dalam rentang waktu tersebut, Lissoii tidak hanya bertahan tetapi juga tumbuh menjadi ruang alternatif yang konsisten merawat tradisi dalam balutan kreativitas modern.
Keberadaannya menjadi bukti bahwa tuak sebagai bagian dari warisan budaya masih relevan dan mampu beradaptasi dengan selera generasi kini.
Adakah teknik penyajian khusus untuk menikmati minuman tuak di sana? Salah satu karyawan di sana bermarga Sianturi dan berusia 23 tahun mengatakan tidak ada campuran apa pun yag mereka gunakan.
Tuak disuguhkan langsung di dalam gelas, murni tanpa tambahan bahan lain—oleh tangan pertama.
Keaslian ini menjadi prinsip yang dijaga demi mempertahankan cita rasa otentik dan untuk menghormati tradisi.
Selain menyuguhkan tuak sebagai primadona, Lissoii juga menyediakan beragam pilihan minuman lain mulai dari bir dan arak hingga teh, kopi, jus, dan air putih.
Ini bentuk keterbukaan terhadap selera kalangan yang majemuk.
Sebagai teman minuman, aneka makanan juga tersedia, mulai dari camilan ringan hingga hidangan berat. Tak ketinggalan, ada juga tambul—makanan pendamping khas, daging antara lain, yang biasa dinikmati bersama tuak.
Yang terakhir ini menegaskan suasana khas lapo Batak.
Lissoii terbuka untuk siapa saja yang ingin menikmati suasana santai dan hangat.
Namun, terdapat satu aturan yang ditegakkan dengan tegas: pengunjung yang masih mengenakan seragam sekolah tidak diperkenankan mengonsumsi tuak di tempat ini.
Ini merupakan bentuk tanggung jawab terhadap publik.

Lintas Generasi
Segmen pengunjung Liisoi campuran anak muda dengan generasi yang lebih sepuh, termasuk lansia.
Isyarat bahwa kafe ini bukan sekadar tempat minum melainkan ruang lintas generasi yang mempertemukan nilai-nilai tradisional dengan semangat kebersamaan masa kini.
Lissoii mulai beroperasi setiap hari dari pukul 15.00 WIB hingga 23.00 WIB.
Rentang waktu ini dipilih agar pengunjung dapat menikmati suasana sore hingga malam hari; masa yang tepat dipakai untuk berkumpul, berbincang, dan bersantai bersama teman maupun keluarga.
Sebagai penyemarak suasana, pertunjukan live musik ada setiap Kamis dan Sabtu, mulai pukul 20.00 hingga 23.00 WIB.
Sajian ini menjadi daya tarik tersendiri—membawa atmosfer yang lebih hangat dan akrab.
Pada sisi lain, menjadi kesempatan berekspresi bagi musisi lokal.
Kata ‘lissoii’ memiliki makna budaya yang mendalam.
Dalam tradisi masyarakat Batak Toba, kata ini kerap diucapkan saat bersulang, sebagai ungkapan kegembiraan dan keakraban—setara dengan cheers dalam budaya Barat atau “kanpai dalam budaya Jepang.
Ucapan ini biasa terdengar ketika gelas tuak diangkat dan diteguk bersama dalam suasana penuh persaudaraan.
Di Lissoii, tuak memang bukan lagi hanya tentang nostalgia masa lalu, tetapi juga ihwal ruang pertemuan, percakapan, dan apresiasi terhadap budaya Batak yang terus hidup dan berkembang.
Kata “Lissoi” juga lekat dengan sebuah lagu daerah populer ciptaan komponis legendaris Nahum Situmorang.
Lagu tersebut menggambarkan suasana akrab masyarakat Batak saat berkumpul dan menikmati tuak di kedai-kedai tradisional.
Dengan lirik “Dongan sapartinaonan, o parmitu [kawan sependeritaaan, O peminum tuak].....
Inum ma tuakmi (Minumlah tuakmu)...
Lissoi...
Lissoi...”—lagu ini menjadi semacam anthem kegembiraan dan pengikat rasa kebersamaan dalam setiap tegukan tuak.
Pemilihan nama Lissoii untuk kafe ini memang tepat. Lapo modern ini bukan hanya tempat menikmati minuman, tetapi juga sebagai ruang untuk merayakan kebudayaan, persahabatan, dan sukacita yang diwariskan secara turun-temurun.
Salah satu keunggulan Lissoii terletak pada lokasinya yang strategis: berada di dekat areal persawahan.
Hamparan tanaman padi di sekeliling menciptakan suasana yang sejuk, asri, dan menenangkan—jauh dari hiruk pikuk kebisingan kota.
Udara yang bersih serta pemandangan terbuka menjadikan Lissoii tempat ideal untuk melepas penat, berbincang santai, atau sekadar menikmati waktu bersama alam dan kawan dalam suasana yang lebih intim.
Tuak yang disajikan di sini berasal dari Sionggang, sebuah nagori [kampung] yang terletak di wilayah Silau Malaha, Kabupaten Simalungun.
Wilayah ini dikenal sebagai salah satu sentra penghasil tuak berkualitas, berkat kondisi alam dan keterampilan lokal yang telah teruji secara turun-temurun.
Tuak yang diproduksi berasal dari dua jenis pohon, yakni aren dan kelapa—masing-masing memiliki karakter rasa dan aroma yang khas.
Menariknya, banyak orang mengira efek memabukkan berasal dari kadar alkoholnya.
Padahal, menurut pengalaman para penikmat setia, sensasi yang muncul justru lebih dipengaruhi oleh aroma fermentasi yang kuat, bukan semata oleh kadar alkoholnya.
Inilah yang menjadikan tuak sebagai minuman tradisional yang unik dan berbeda dari minuman beralkohol pada umumnya.
Lissoii saat ini dikelola oleh empat orang karyawan, terdiri dari satu perempuan dan tiga laki-laki.
Mereka tidak hanya bertugas melayani pengunjung tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga atmosfer hangat dan kekeluargaan yang menjadi ciri khasnya.
Kehadiran tim yang solid dan ramah turut menciptakan suasana akrab yang membuat pengunjung merasa betah dan ingin kembali.
Ada juga pengunjung yang datang bukan untuk menikmati tuak, melainkan sekadar singgah untuk mereguk pesona pemandangan hijau sambil menyantap camilan ringan.
Ada juga yang berkunjung hanya untuk menemani seseorang atau menikmati suasana atau berbincang.
Sebaliknya, banyak juga yang hadir demi tuak.
“Bagi saya, ada perasaan berbeda ketika berbicara tanpa ditemani gelas berisi tuak. Seolah ada jarak yang belum mencair,” ujar salah-satu pengunjung bermarga Manihuruk dan berumur 25 tahun.
Tuak, dalam konteks Kafe-Lapo Lissoii bukan semata minuman—melainkan media pembuka percakapan, jembatan spontanitas, dan pemantik keakraban yang tumbuh secara alami di antara gelas-gelas yang terangkat.
Di sudut sebuah lapo [kedai] kecil di Siantar merebak aroma tuak segar yang baru saja dituangkan ke dalam gelas bening.

Benny Tambak—pegiat budaya sekaligus penikmat tuak sejak muda—duduk santai di bangku kayu.
Matanya menyorot raut wajah kawan-kawan yang sedang berbincang hangat di sekitarnya.
Percakapan ihwal apa saja: keluarga, dinamika sosial di kampung, hingga politik nasional dan internasional.
Sungguh, di tempat seperti inilah suara-suara yang sering terpinggirkan menemukan ruangnya.
Ditemani tuak, perbincangan niscaya bertambah seru.
“Tuak itu bukan hanya soal rasa,” ujar Benny Tambak pelan, “tapi juga tentang bagaimana kita menjaga ruang bicara yang jujur dan kesetaraan di tengah masyarakat.”
Aktif memperkenalkan kembali tuak di tengah derasnya arus modernisasi, ada satu kalimat yang selalu ia bawa ke mana pun: “Tuak from God.”
Kalimat itu bukan sekadar ucapan iseng atau slogan promosi.
Ia adalah wujud keyakinan mendalam bahwa minuman yang satu ini bukan hanya hasil fermentasi alam melainkan karunia yang menyimpan makna: datang dari alam sebagai pemberian Tuhan sehingga pantas untuk dinikmati.
“Tuak itu bukan racun, asal tahu cara meminumnya. Ini bukan sekadar minuman, tapi media yang mempertemukan orang, menjembatani obrolan, sekaligus merawat nilai-nilai kita,” tutur Benny, yang selama bertahun-tahun rutin menggelar diskusi, pertunjukan budaya, dan festival kecil dengan tuak sebagai pengikatnya.
“Kalau kopi punya warung kopi, kenapa tuak tidak boleh punya ruang yang layak?” tanyanya pada satu malam di salah satu lapo favoritnya. “Kita butuh ruang—bukan untuk mabuk-mabukan, tapi untuk mendengar dan didengar. Tuak hanyalah perantara.”
Lebih dari sekadar minuman, menurut dia, tuak mengandung nilai simbolik tinggi: sumber semangat sekaligus lambang keakraban.
Dan, dalam konteks adat, minuman ini hadir dalam posisi sakral di pelbagai perhelatan.
Mulai dari pesta pernikahan hingga mangongkal holi [menggali tulang-belulang leluhur untuk dipindahan ke tugu keluarga].
Meruntuhkan Stigma
Ketertarikan Benny pada tuak muncul sejak ia masih remaja.
Ia tumbuh di wilayah sentra pohon aren, tempat sebagian besar penduduk bekerja sebagai paragat [penderes tuak].
Awalnya ia hanya ikut-ikutan mencicipi demi suasana.
Namun, lama-kelamaan ia menyukainya—bukan karena candu, melainkan karena minuman tersebut telah menjadi bagian dari irama sosial dan budaya.
Kini, bukan hanya penikmat. Dia juga ikut menjual, menyuguhkan, dan sekaligus menyulap ruang minum menjadi ruang berpikir.
Langkah itu tidak mudah.
Ia harus meruntuhkan stigma.
Ia mengemas tuak dengan cara baru tanpa menghilangkan rasa aslinya.
Ia bekerja sama langsung dengan paragat, memastikan proses penyadapan berjalan alami dan etis, serta membeli dari mereka lalu menjual ke berbagai tempat.
Dalam pengamatan Benny, saat ini kalangan mudalah kelompok terbesar peminum tuak di berbagai lapo.
Bagi mereka, tuak adalah alternatif paling pas.
Bukan semata karena kandungan alkoholnya, melainkan karena akses yang mudah dan harga yang jauh lebih terjangkau dibanding minuman kemasan beralkohol.
Meski harga tuak telah berubah, dari Rp1.500 dulu menjadi Rp3.000 per gelas, itu tetap saja masih murah.
Proses menikmatinya pun praktis: cukup singgah ke lapo terdekat, duduk, lalu meneguknya dalam suasana akrab.
Kombinasi harga ramah kantong dan atmosfer menjadikannya pilihan utama untuk melepas penat, menjalin pertemanan, atau sekadar mengisi waktu luang.
Fenomena ini menandakan bahwa tuak tidak hanya bertahan sebagai minuman tradisional tetapi juga berhasil menarik minat generasi muda dan menemukan tempatnya dalam gaya hidup mereka saat ini.
Bagi Benny, tuak melampaui wujudnya sebagai minuman.
Dalam kebudayaan Batak, ia menjadi simbol kebersamaan, jejak identitas yang diwariskan turun-temurun, dan jembatan relasi sosial.
Juga, teman dalam obrolan sederhana hingga percakapan komunitas yang penuh makna.
Simpul Sosial
Dalam masyarakat Batak, tuak memiliki dimensi mitologis yang mendalam.
Dikisahkan seorang gadis miskin yang harus menjadi istri kelima seorang juragan kaya untuk melunasi utang keluarganya. Ia menolak takdir itu dengan berkata: "Jika aku mati, jangan kuburkan jasadku.Aku akan menjadi pohon yang bermanfaat sepanjang masa."
Setelah ia meninggal, tumbuhlah pohon aren—sumber air nira untuk tuak.
Air yang menetes dari batangnya dipercaya sebagai air mata sang gadis, penanda cinta dan pengorbanan abadi.
Kini, tuak menjelma menjadi bagian dari tren dan gaya hidup tanpa kehilangan akar budayanya.
Meski stigma negatif masih ada, penting diingat bahwa ia berasal dari alam—pemberian Tuhan. Ia menjadi teman bersantai sekaligus penghangat suasana.
Soal rasa, tentu itu subjektif dan bergantung selera. “Bagi saya, tuak yang enak adalah yang terasa sodanya—karbonasi alami dari fermentasi yang pas, menyegarkan dan ringan,” kata Banny Tambak.
Jika ditambah raru (kulit kayu pahit), cita rasanya berubah lebih kuat, berkarakter, dan memberi kedalaman kompleks yang disukai penikmat berpengalaman.
Selain alami, tuak juga unggul secara ekonomi. Harganya jauh lebih terjangkau dibanding teh, kopi, atau minuman beralkohol modern. Cita rasanya yang kuat dan aroma tajam menjadikannya tak mudah dilupakan.

Suasana yang adem di kafe Lissoi (Foto:Novriani)
Dalam budaya Batak, lapo menjadi arena marmitu—minum tuak sambil bernyanyi dan berbagi cerita.
Suasana ini menciptakan keakraban hangat, tempat segala hal bisa dibicarakan dengan terbuka.
Bahkan dalam momen pemilihan kepala desa, kedai ini sering berubah menjadi ruang kampanye informal yang menjembatani komunikasi antara pemimpin dan rakyat, tanpa sekat protokoler.
Lapo, atau pakter tuak, pada akhirnya bukan sekadar tempat menikmati minuman tradisional. Ia adalah ruang penting yang meruntuhkan sekat-sekat sosial.
Di sini, tak penting usia, profesi, atau status ekonomi—semua bisa duduk di meja yang sama, mengangkat gelas, dan berbicara dari hati ke hati.
Sebagai salah satu tokoh yang aktif memperkenalkan kembali tuak dalam format lebih modern dan terbuka, Benny percaya berpendapat bahwa lapo itu simpul sosial yang tak boleh hilang.
Lewat inisiatif komunitas dan festival, ia bersama rekan-rekannya berupaya merawat tradisi tua ini agar tak lekang ditelan zaman.
Ia lantas berpesan, terutama kepada generasi muda, agar melestarikan tuak. Langkahnya dapat dimulai dari yang sederhana namun bermakna.
Pertama, menciptakan wadah yang layak—seperti lapo, warung, atau kafe—dengan konsep terbuka dan inklusif.
Bukan sekadar tempat menjual tuak, tetapi titik temu budaya dan ruang perjumpaan lintas generasi.
Kedua, memanfaatkan media sosial untuk promosi: lewat video pengenalan, dokumentasi proses pembuatan, atau kisah-kisah tradisi yang dibagikan di Instagram, TikTok, YouTube, dan yang lain.
Ketiga, menyelenggarakan festival budaya, seperti Tuak Fest 2014, yang mempertemukan para pegiat dari berbagai wilayah.
Cara ini memperkuat kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga tradisi lokal.
Dalam pikiran Benny, tuak bukan sekadar cairan fermentasi—melainkan jembatan antara masa lalu dan masa depan, antara suara yang nyaring dan suara yang kerap luput terdengar.
Di lapo, ia menemukan ruang paling jujur untuk menjadi manusia—ruang di mana semua orang duduk setara, berbicara apa adanya, dan merasa didengar.
Di antara gelas-gelas kecil yang tak pernah benar-benar kosong, Benny Tambak merawat sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar minuman: ia menjaga warisan, membangun ruang, dan menanamkan makna. (Tamat)
===
Penulis: Novriani Tambunan, Indah Cahyani, Alberto Nainggolan—peserta Sekolah Jurnalisme Parboaboa (SJP) Pematangsiantar, Batch 2. SJP merupakan buah kerja sama Parboaboa.com dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).
**CATATAN EDITOR
Tulisan ini direpublikasi dari media Parboa-boa pada 10 februari 2026 pukul 00.55 WIB. Tulisan terdiri dari 3 bagian yang dipublikasi bersamaan. LINK: https://parboaboa.com/jejak-budaya-batak-dalam-gelas-dan-dialog