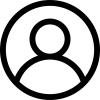Oleh Febrina Galuh Permanasari *
INDEPENDEN---Ingin berbagi catatan dari konferensi yang fokus mendiskusikan tentang interseksi jurnalisme dan teknologi pada negara-negara selatan (Global South). Konferensi ini diberi judul CTRL+J International, dan dilaksanakan di Kuala Lumpur pada 19 November 2025.
Acara di Kuala Lumpur ini menjadi penutup dari rangkaian pertemuan regional yang sebelumnya diadakan CTRL+J di Sao Paulo, Jakarta, dan Johannesburg. Mempertemukan jurnalis, ahli teknologi, peneliti, dan pembuat kebijakan untuk merumuskan solusi yang ambisius namun mendesak: menggeser perbincangan dari keluhan individu menjadi aksi kolektif, mencari solusi nyata bagi jurnalisme yang terkepung oleh disrupsi teknologi.
Dari sesi diskusi dan percakapan di sela-sela acara, saya makin menyadari bahwa jurnalisme berada di sebuah titik kritis. Ditambah masifnya perkembangan AI, bisa jadi memicu kepunahan media berkepentingan publik atau mengkatalisasi ekosistem informasi yang lebih adil dan baru. Pilihan antara kepunahan dan imajinasi ulang inilah yang menjadi latar belakang setiap diskusi.
Setidaknya ada tiga pelajaran kunci yang saya dapatkan yang menantang asumsi umum tentang arah media kita, dengan fokus pada tantangan unik dan solusi inovatif yang mungkin lahir dari perspektif Global South.
Pertama, konsensus yang terbentuk bahwa jurnalisme adalah barang publik esensial yang tengah menghadapi "kegagalan pasar struktural".
Para pembicara sepakat bahwa model bisnis jurnalisme tidak dapat lagi ditopang oleh kekuatan pasar semata. Runtuhnya pendapatan iklan tradisional yang kini beralih ke platform teknologi raksasa telah menciptakan krisis keberlanjutan yang akut.
Namun, kegagalan pasar ini diperparah oleh krisis lain yang tak kalah pelik, yaitu ketergantungan struktural pada platform teknologi yakni mengontrol informasi apa yang dilihat dan tidak dilihat oleh publik.
Laporan CTRL+J APAC yang dibahas di Jakarta memberikan gambaran suram tentang dampak nyata dari krisis ini.
Media lokal di Indonesia, misalnya, melaporkan penurunan trafik situs web hingga 50 persen sejak peluncuran berbagai alat AI generatif. Lebih parah lagi, terungkap bahwa hampir 30 persen trafik ke situs web media berasal dari bot AI yang terus-menerus "memanen" konten, memaksa media membayar kapasitas infrastruktur yang lebih besar.
Masalah ini bukanlah fenomena lokal, melainkan sebuah tren global yang sistemik. Laporan terbaru dari Reuters Institute untuk tahun 2025 mengonfirmasi bahwa trafik rujukan dari Facebook telah anjlok sebesar 67 persen dalam dua tahun terakhir, sementara trafik dari X (sebelumnya Twitter) turun 50 persen. Dengan demikian, media di Global South kini menghadapi ancaman eksistensial ganda: model bisnis yang fondasinya telah runtuh dan kontrol atas distribusi konten yang sepenuhnya berada di tangan segelintir raksasa teknologi.
Kedua, Artificial Intelligence (AI) adalah pedang bermata dua.
Perdebatan di Kuala Lumpur mencerminkan dilema ini. Di satu sisi, ancamannya sangat nyata seperti banjirnya konten AI berkualitas rendah di internet, pelanggaran hak cipta, dan kekhawatiran akan hilangnya pekerjaan jurnalis.
Kekhawatiran ini bukan sekadar soal teknis, melainkan juga etis, karena potensi bias dan 'kolonialisme data' terhadap narasi dari Global South, belum lagi hak atas konten yang diakses oleh tanpa izin oleh AI bot. Namun, sejalan dengan semangat CTRL+J, tantangan ini harus diubah jadi peluang, yaitu bagaimana Global South tidak hanya menggunakan AI, tetapi juga tentang memiliki dan membentuknya.
Hal ini terungkap dalam panel berjudul “Conversation between two durians: Winning the AI Ownership Battle", yang menampilkan Shuwei Fang, Shorenstein Fellow at the Harvard Kennedy School dan Karen Hao, seorang jurnalis dan penulis buku Empire of AI.
Fang membawa perspektif menarik bahwa selama bertahun-tahun, kita berdebat tentang hubungan simbiosis sekaligus parasitisme dengan platform media sosial. Ternyata, kita mungkin telah berdebat dengan lawan yang salah. Musuh atau mitra utama kita berikutnya bukanlah platform, melainkan AI itu sendiri.
Fang menjelaskan pergeseran fundamental dari model distribusi B2B2C (Business-to-Business-to-Consumer), di mana platform seperti Facebook menjadi perantara, ke model B2A2C (Business-to-Agent-to-Consumer). Dalam model baru ini, "Agen" AI menjadi perantara baru antara publisher dan audiens.
Perbedaannya sangat krusial. Platform hanya menyortir dan mengirimkan. Sedangkan AI, di sisi lain, memiliki apa yang disebut Fang sebagai "agensi fungsional". Artinya, AI tidak hanya mendistribusikan, tetapi secara aktif membuat keputusan.
Sedangkan Karen Hao menggaris bawahi bahwa perusahaan AI telah membentuk sebuah imperium kekuasaan berbasis data, modal, dan kontrol infrastruktur digital, yang tumbuh melalui riset yang dimodifikasi kepentingan bisnis, eksploitasi tenaga kerja tak terlihat, dan sistem algoritmik yang penuh bias, sekaligus memperdalam ketimpangan global. Karen mendorong agar terbentuknya kapabilitas internal terutama di negara Global South, sehingga mengurangi ketergantungan pada platform AI besar dan menyeimbangkan kembali sistem pasar.
Ketiga, Global South seharusnya bukan jadi footnote (catatan kaki), tapi asal dari solusi.
Selama ini, narasi yang beredar adalah negara-negara di Global South hanya bisa bereaksi terhadap tren teknologi yang datang dari Barat. Dari São Paulo hingga Jakarta, saya melihat gelombang inisiatif proaktif di mana negara-negara Selatan tidak lagi menunggu, melainkan secara aktif membentuk masa depan mereka sendiri melalui kebijakan dan regulasi.
Beberapa contoh konkret yang menonjol misalnya di Brasil, yang telah menyetujui RUU tentang AI. Regulasi ini mencakup kewajiban transparansi bagi pengembang AI untuk menginformasikan konten berhak cipta yang digunakan, serta menjamin hak remunerasi bagi pembuat konten. Ini adalah langkah maju yang signifikan.
Di Indonesia, ada Peraturan Presiden tentang "Publisher Rights" telah menjadi landasan hukum yang kuat. Regulasi ini memaksa platform untuk duduk semeja dan bernegosiasi secara adil dengan para penerbit media, memberikan posisi tawar yang belum pernah ada sebelumnya.
Di Afrika Selatan, ada pendekatan yang lebih radikal. Penyelidikan pasar oleh Komisi Persaingan di sana tidak hanya menuntut kompensasi finansial, tetapi juga perubahan struktural pada cara platform beroperasi. Mereka menyoroti desain algoritma yang anti-persaingan dan menuntut reformasi yang lebih mendasar.
Jika ada satu tema yang paling menonjol dari seluruh rangkaian acara CTRL+J, itu adalah pergeseran dari aksi individual ke aksi kolektif. Indonesia mungkin bisa meniru model Brazil dengan perlindungan hak cipta karya jurnalistiknya.
Hal yang sama diutarakan oleh Dr. Andry Indrady, selaku Direktorat Jenderal di Kementerian Hukum Indonesia dalam pidatonya. Ia mendukung upaya pengakuan hak cipta atas karya jurnalistik, namun perlu dibentuk konsensus bersama mengenai jenis konten, standarisasi, dan sistem yang akan dipakai, karena saat ini baru ada aturan hak cipta untuk konten tulis, foto, dan audio/video, yang seharusnya bisa jadi dasar atas konten jurnalistik.
Meskipun tantangan yang kita hadapi sangat besar, ada nuansa optimisme yang kuat. Ada gelombang energi baru yang kolaboratif, inovatif, dan proaktif yang datang dari Global South. Kita tidak lagi hanya menjadi objek dari perubahan teknologi, kita adalah subjek yang akan membentuknya.
Saat AI menjadi penjaga gerbang informasi yang baru, pertanyaannya bukan lagi apakah kita bisa bertahan, tetapi bagaimana kita secara kolektif mencari solusi bersama untuk membentuk masa depan di mana teknologi melayani kepentingan publik, bukan sebaliknya.
---
*Febrina Galuh Permanasari adalah Direktur Eksekutif Aliansi Jurnalis Independen (AJI), pemerhati isu kebebasan pers, cek fakta, dan pengembangan jurnalis di Indonesia dan Asia Tenggara. Saat ini dia sedang menempuh Pendidikan Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia.