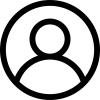Oleh Ayu Sulistyowati
INDEPENDEN – Siswa-siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jurusan kelautan dan perikanan saat praktik kerja lapangan (PKL), tak hanya menghadapi gempuran gelombang samudera di atas kapal tetapi juga rentan dieksploitasi bahkan diperdagangkan.
Mereka dipaksa menahan pedihnya bekerja lebih dari 8 jam sehari, tanpa mengenal pagi, siang, malam. Mereka harus mempertaruhkan kesehatan fisik dan non-fisik, terisolasi dari sinyal telekomunikasi apa pun dan jauh dari pengawasan yang menjadi kewajiban sekolah.
Seakan karena sekolah jurusan kelautan, ya harus praktik di tengah laut, terlepas apa pun risiko yang mereka hadapi.
Sebagai ABK, bukan PKL SMK
“Yang saya pikirkan itu bagaimana cara pulang. Saya tidak mau melaut sebagai ABK (anak buah kapal atau kelasi). Saya ke sini (Benoa) bersama teman-teman itu untuk PKL. Kenapa malah menjadi ABK, ya… saya bingung,” kata Adi (18), siswa asal Jawa Tengah.

Adi ini salah satu siswa yang dibatalkan melaut dengan kapal penangkap cumi milik PT Bandar Nelayan oleh Syahbandar Perikanan Pos Pelayanan Kapal Perikanan Pelabuhan Benoa, Bali, akhir Juni 2025.
Selain Adi, ada juga delapan siswa lainnya yang juga ada dari Jawa Barat dan Kalimantan Timur. Mereka semua batal melaut karena perbedaan dokumen yang dipegang Syahbandar dengan kenyataan sebagai siswa PKL SMK kelautan.
Konon dokumen yang dimasukkan perusahaan tempat Adi magang ke Syahbandar adalah KTP yang menunjukkan dia sudah berusia 18 tahun dan juga dokumen BST yang menunjukkan kalau Adi sudah ikut training di tahun 2024.
Padahal Adi tidak pernah ikut pelatihan keamanan kerja untuk mendapatkan buku BST sebagai syarat memiliki Buku Pelaut. Jangankan training, PKL saja dia belum selesai.
Kepala Syahbandar Perikanan Pos Pelayanan Kapal Perikanan Pelabuhan Benoa, Habibi mengatakan ia mendapatkan informasi adanya siswa PKL tersebut justru setelah dokumen lolos ditandantanganinya.
Harusnya siswa PKL akan didata sebagai Kadet (sebutan jabatan siswa PKL di kapal perikanan) bukan Kelasi. Karena ternyata Adi dan 8 siswa itu adalah PKL SMK, maka ia memutuskan membatalkan dan meminta pihak kapal menurunkannya.
"Jika sebagai PKL SMK, perusahaan harus melampirkan surat keterangan dari sekolah. [Karena] ada KTP yang sudah 18 tahun ke atas dan memiliki BST dan Buku Pelaut, yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, permohonan dari perusahaan kapal juga ada maka kami mengesahkan [mereka dengan] jabatan sebagai Kelasi (ABK). Kami tidak tahu mereka adalah siswa PKL SMK,” kata Habibi, di kantornya, Selasa (1/7/2025).
Berkaca dari temuan ini, Habibi pun memutuskan untuk lebih atensi dengan data serta KTP kelengkapan dokumen dari perusahaan yang masuk mendapatkan pengesahan siapa saja ABK yang akan bekerja di kapalnya. Ia menjelaskan selama ini dokumen yang masuk yang membedakan Kelasi dan Kadet hanya di lampiran surat pengantar dari sekolah.
Nah, lampiran dari sekolah tersebut memang tidak semuanya siswa sudah memiliki KTP. Siswa PKL SMK ini ada yang masih berusia 16 tahun dan lolos dapat melaut dengan tetap memiliki buku BST dan Pelaut dengan catatan siswa PKL.
Pihak Habibi tidak bisa memastikan KTP asli atau palsu.
“Karena sistem kami sama sekali belum terintegrasi dengan Kementerian Dalam Negeri atau Dinas Kependudukan untuk cek NIK (nomor induk kependudukan) maupun kementerian terkait lainnya. Sistem kami masih manual hingga sekarang,” jelasnya.
Maka, menurut Habibi, ia tidak bisa menjanjikani mencegah adanya praktik pemalsuan data, pemanfaatan data, sampai rawannya siswa-siswa ini diperdagangkan karena hal ini tidak bisa dilakukan oleh lembaganya sendirian.
Ia sepakat jika perusahaan-perusahaan penyalur tenaga kerja, khususnya diperikanan harus lebih maksimal menyortir dan bukan malah seperti menjalankan praktik calo tenaga kerja dengan melegalkan segala cara demi potensi rupiahnya.
Adi dan delapan siswa lainnya itu datang diantar guru sekolahnya bersama belasan temannya dan dititipkan kepada seorang yang dikenalkan sekolah sebagai pembimbing lapangan.
Oleh si pembimbing lapangan bernama Abdul Rohman ini, mereka ditempatkan di sebuah rumah bersekat-sekat tanpa isi parabotan. Mirip seperti kamar kos-kosan berdinding sebagaian papan triplek, sebagian lainnya tembok. Namun ada pula kamar yang semuanya dinding tembok.
Memang ada jendela, hanya saja ketika dibuka pemandangannya tembok tetangga. Ruangan sekat-sekat itu bervariasi luasannya kisaran 3 meter x 4 meter. Dan ruangan itulah, Adi dan belasan siswa diinapkan. Mereka mendapatkan makanan nasi bungkus setiap hari dua kali per 9 pagi dan 5 sore dari janji dua kali sehari. Nasi bungkus itu berisi lauk hampir sama setiap harinya, ayam sepotong kecil atau suwiran ayam, sedikit sambel, sedikit mi goreng, ya, intinya serba sedikit termasuk sekepal nasi.
Bahkan, sebelum mereka datang sudah ada belasan siswa lainnya dari SMK daerah lain tinggal lebih dari sepekan. “Ya, itu tempat sementara gitu katanya. Kan, nunggu giliran panggilan dari Bapak yang katanya pembimbing lapangan itu. Giliran naik kapal buat melaut, lah…,” sahut teman Adi yang usianya lebih muda, 16 tahun.
Siswa yang masih berusia kurang dari 18 tahun belum bisa melaut juga mengalami masa menunggu seperti ini. Teman Adi tersebut mengeluhkan bagaimana dengan nasibnya di mes.
“Lah, apa saya bakal dua tahun di mes ini buat menunggu 18 tahun untuk melaut? Saya bingung. Kan, saya mau PKL untuk bisa lulus sekolah. Bingung saya…,” keluhnya sebagaimana ditirukan Ari.
Pengalaman Ari ini berbeda dengan Arya (17), siswa PKL SMK dari Jawa Timur, pertengahan April 2025.
Ia bersama beberapa temannya melaut dengan kapal kolekting dari Benoa. Mereka diantar, didrop dan diserahterimakan di kapal milik perusahaan perikanan di Benoa. Arya bersama temannya tidak diinapkan di mess, tetapi langsung masuk ke kapal, tinggal beberapa hari dan langsung melaut, awal Mei 2025.
Arya bersama teman-temannya berangkat. Kapal kolekting itu tarik jangkar.
Para siswa yang ditemui Independen.id, direntang bulan Februari 2025-Juli 2025, membeberkan pengalaman berkehidupan melaut di atas kapal. Ada melaut dengan kapal kolekting, kapal penangkap cumi, kapal penangkap ikan atau apa saja kapal yang bersedia menerima PKL dan rata-rata merupakan pengalaman pertama mereka melaut.
Mereka harus melawan kerasnya ombak, mabuk laut, gatal-gatal, kesakitan hingga “bekerja” tak lagi sesuai kompetensinya atau yang dipejari di sekolah.
Pesan yang terngiang dari sekolah maupun kakak kelasnya : “Jangan cengeng! Harus kuat dan pintar-pintar jaga diri biar selamat”. Dan pesan orang tua agar bisa menjaga diri.
Lebih dari dua minggu kemudian dari pertemuan April 2025, Arya dan teman-temannya merapat kembali dan bongkar muat di Benoa. “Melihat dan menginjak daratan setelah melepas jangkar itu lega. Rasanya ingin segera pulang tanpa harus balik lagi. Tapi, masa PKL-nya enam bulan, dan saya bersama teman-teman ini baru dapat melaut itu sebulanan. Jadi, ya…harus lanjut… melaut lagi. Mungkin minggu depan atau nunggu perintah kapal saja kapan berangkat. Soal tinggal, ya, tetap di kapal,” kata Arya.
Ketika itu, Arya bersama tujuh kawan satu sekolahnya baru saja kembali berlabuh di Pelabuhan Benoa, Bali. Mereka tengah menjalani PKL selama enam bulan di atas kapal kolekting dengan tugas menjemput ikan hasil tangkapan kapal di tengah laut, serta membawakan logistik untuk kapal tersebut.
Hampir sebulanan di atas kapal, ternyata tak seperti apa yang dibayangkan oleh siswa itu sendiri. Karena hampir jauh dari apa yang mereka pelajari di sekolah. (Baca : https://independen.id/pkl-smk-di-laut-modus-eksploitasi-berkedok-pendidikan dan https://independen.id/anak-di-tengah-samudra-celah-kebijakan-yang-dimanfaatkan-bag-2)
Seakan memang tak ada kata lain, hanya bisa pasrah, menerima tanpa berani bertanya kepada guru atau siapa pun. Hanya berusaha menahan kesabaran untuk bisa segera selesai, dari bulan ke bulan, pulang dan lulus.
Di bawah kuasa “calo” dan sekolah
Jauh dari rumah. Lintas provinsi. Lintas pulau. Tanpa jaringan komunikasi di tengah lautan. Seperti tahanan laut. Meski sebagian anak SMK itu sudah berusia 18 tahun, mental mereka belum siap menghadapi kerasnya pekerjaan di atas kapal.
“Sebenarnya ada Starlink di atas kapal. Tetapi yang memiliki akses jaringannya hanya nahkoda dan kepala kapal saja. Kami hanya berharap ada sinyal nyangkut ketika merapat beberapa mil dari daratan itu ada nyangkut-nyangkut sinyal dikit. Tapi itu, kan, tidak setiap hari. Bisa beberapa minggu kemudian atau bulanan dapat sinyal begitu,” cerita Wahyu (23) asal Nusa Tenggara Barat (NTB).
Namun, mereka hanya bisa pasrah dan tidak kuasa mengadu. Ke orang tua pun tidak berani. Khawatir justru membebani pikiran orang tua mereka. Orang tua juga sudah menandatangai surat pernyataan membolehkan anak mereka menjalani PKL bersama perusahaan yang menyalurkan di pelabuhan pilihannya bersama sekolah.
Anak PKL SMK ini, lagi-lagi, hanya bisa menuruti apa arahan dari sekolah. Mereka diantar guru atau kepala program PKL dari sekolah ke pelabuhan tempat kapal-kapal praktik melaut. Ditemani selama perjalanan dari sekolah ke pelabuhan, salah satunya Pelabuhan Benoa. Lalu, anak-anak ini diserahkan kepada pengurus kapal dan ditinggalkan.
Nah, ada pula anak-anak PKL SMK ini diantar guru, sesampainya di kota tujuan, mereka diserahterimakan dengan orang yang dikenalkan sebagai pembimbing lapangan. Padahal, bisa jadi pembimbing lapangan itu bisa jadi perusahaan penyalur tenaga kerja, entah berbadan hukum atau tidak atau bisa jadi memang “calo”.
Pembatalan keberangkatan 9 anak PKL SMK asal Jawa Tengah oleh Syahbandar Pelabuhan Benoa pada akhir Juni 2025 diduga melalui perusahaan penyalur tenaga kerja yang tidak sah
Anak-anak ini tidak mendapatkan haknya untuk paham soal PKL baik dari sekolah maupun penyalur. Bahkan, orang tua atau wali mereka pun mengaku hanya tahu sebatas anak mereka harus menjalani PKL di tengah laut di Benoa, dan diminta mentransfer sejumlah uang untuk proses PKL tersebut.
Salah satu orang tua mengaku khawatir setelah mendapatkan kabar mengenai anak PKL ini didaftarkan sebagai Kelasi bukannya sebagai Kadet. Padahal, semua orang tua atau wali telah menandatangain surat pernyataan memberikan ijin anak untuk mengikuti proses PKL.
“Aduh, kami bingung sebagai orang tua. Sekolah juga katanya traning untuk BST itu bisa cukup melihat dari You Tube saja. Aduh, bagaimana ini ya… Sudahlah…yang penting pulang dulu, kali ya…,” kata orang tua salah satu pelajar yang tidak mau disebutkan namanya.
Kepala SMK Yos Soedarso Sidareja, Cilacap, Muhyasin, ketika dikonfirmasi Independen.id soal pembatalan beberapa anak PKL dari sekolahnya karena perbedaan dokumen yang ditemukan Syahbandar dengan yang diajukan perusahaan justru berbalik bertanya.
“Info dari mana ini? Perbedaan dokumen apa? Tidak ada itu perbedaan dokumen. Semua juga terserah kami mau bekerja sama dengan perusahaan mana saja,” katanya ketika dihubungi melalui WhatsApp dan pembicaraan via telepon.
Ia juga menjelaskan kalau siswanya dipulangkan karena ada perbedaan peraturan kebijakan dari kepala pelabuhan yang hanya menjatah 4 siswa saja berangkat ikut kapal. Oleh sebab itu, anak-anak dipulangkan kembali dari Bali, guna mengurangi biaya hidup selama di mess/penampungan perusahaan.
Sementara Habibi menjelaskan adanya perbedaan dokumen dan sebaiknya diselesaikan pihak sekolah dan perusahaan yang diajak kerja sama mengenai program PKL ini. Dan hingga awal Juni 2025, belum ada perubahan kebijakan terkait pengajuan program PKL SMK ini dan belum ada kebijakan soal pembatasan jumlah siswa PKL SMK, khususnya di Benoa, Bali.
Ari bersama teman-temannya bercerita mereka takut dengan orang yang dikenalkan sebagai pembimbing lapangan yang meminta untuk tidak mengaku sebagai anak PKL SMK.
Mereka harus mengaku sebagai Kelasi/ABK dan tidak perlu membantah apa pun untuk menunggu panggilan masuk hingga pergi melaut.
“Kami ini tidak pernah spesifik belajar menangkap cumi atau ikan. Itu hanya sebatas pengetahuan. Kami mempelajari teknik permesinan, teknik memperbaiki jaring ikan,” cerita Ari dari jurusan teknikal kapal penangkap ikan. Teman lainnya dari jurusan nautika kapal penangkap ikan juga bingung mengapa saat naik kapal ditugaskan menangkap cumi, padahal ia mempelajari navigasi kapal.
Dari penelusuran berbagai media terkait siswa PKL SMK kelautan, terdapat beberapa pemberitaan, di antaranya kasus siswa PKL SMK Temon, Kulon Progo yang kabur pada 2020 karena tidak tahan dengan perlakuan dan beban kerja di kapal penangkap cumi. Kemudian pada 23 Mei 2025 diberitakan seorang siswa PKL hilang di perairan Pati, dan pada awal Juli 2025 siswa SMK Negeri 3 Tegal juga hilang saat PKL di atas kapal.
Sekolah dan perusahaan yang diajak kerja sama, atau bahkan yang melibatkan “calo”, tampak sangat berkuasa atas kehidupan anak-anak program PKL SMK ini. Apakah ada pemanfaatan kebijakan yang justru mengalahkan hak-hak siswa sebagai manusia maupun hak anak, terutama bagi mereka yang masih di bawah 18 tahun?
Prosedur yang “kabur”
Anak-anak yang pernah menjalani PKL SMK di tengah laut pada Februari hingga Juli 2025, baik di atas kapal penangkap cumi maupun kapal kolekting, mengatakan mereka tertekan dengan situasi orang tua yang sudah mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk biaya program PKL, serta tekanan dari pihak sekolah dan lingkungan kerja di kapal. Mereka pun berada dalam dilema.
Bagaimanapun, mereka menyadari orang tua telah mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk biaya PKL. Biaya yang diminta sekolah dan perusahaan beragam, mulai dari sekitar satu juta rupiah hingga belasan juta rupiah. Beda SMK, beda pula besarnya biaya.
Di salah satu SMK kelautan di Jawa Tengah, misalnya, sekolah meminta orang tua membayar Rp 3.685.000 per anak, sedangkan subsidi PKL dari Dana BOS hanya Rp 50.000 per anak. Maka orang tua harus menanggung Rp 3.635.000.
Tak hanya itu, orang tua juga harus membayar sekitar Rp 3 juta untuk biaya pelatihan dan mendapatkan buku basic safety training (BST). Buku tersebut menjadi syarat agar anak PKL SMK bisa memiliki buku pelaut untuk dapat “belajar” di atas kapal. Persyaratan itu kemudian menjadi lampiran-lampiran di Kantor Syahbandar.






Laode Hardiani, Tim DFW Indonesia untuk Bali, tak menyangka di tengah kerasnya kehidupan pekerja ABK di Pelabuhan Benoa, mendapati anak PKL SMK terdaftar sebagai ABK. Hal ini hampir saja terjadi saat keberangkatan di akhir Juni 2025.
“Selama ini kami masih fokus menginventarisasi permasalahan pekerja perikanan di Benoa, dan pekerja tentunya sudah berusia dewasa. Kami kaget ketika benar-benar mendapati anak sekolah yang seharusnya terdata sebagai anak PKL justru menjadi pekerja dewasa,” kata Laode.
Ia tak tega melihat anak-anak tersebut tidak berdaya menghadapi ancaman dan tekanan dari pihak yang disebut pembimbing lapangan di Benoa. Ia pun tak habis pikir bagaimana sistem atau proses pelaksanaan PKL SMK kelautan ini selama ini berlangsung. “Bagaimana tanggung jawab pihak sekolah dalam proses pelaksanaan PKL SMK ini? Bagaimana pengawasan dan perlindungan sekolah terhadap anak-anak ini?” lanjutnya dengan sedih.
Usia anak PKL tersebut memang 18 dan 19 tahun. Mereka akhirnya diturunkan dan tidak diberangkatkan oleh Syahbandar. Namun, menurut Laode, meskipun usia mereka sudah bukan anak-anak dan telah memiliki KTP, status mereka tetap pelajar SMK yang diberangkatkan sekolah untuk PKL sebagai bagian dari program uji kompetensi. Karena itu, lanjutnya, pihak perusahaan penyalur seharusnya menaati aturan pelaksanaan PKL.
Pelaksanaan PKL SMK saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020 tentang Praktik Kerja Lapangan Bagi Peserta Didik, serta Panduan Praktik Kerja Lapangan sebagai Mata Pelajaran dalam Implementasi Kurikulum Merdeka, Edisi Revisi Tahun 2024, Direktorat SMK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2024.
“Entah, ya, seperti tumpang tindih begitu. Memang membutuhkan kajian mendalam untuk menganalisis kebijakan-kebijakan mengenai nasib program PKL SMK kelautan ini saat melaut,” kata Laode.
Menurutnya, anak PKL SMK seharusnya mendapat pemahaman maksimal terkait tugas dan tanggung jawab selama PKL di atas kapal: jenis pekerjaan yang akan dilakukan, upah kerja yang akan diterima, serta—yang terpenting—tetap berada dalam pengawasan dan perlindungan sekolah. Bukan sekadar diproses programnya, siswa diturunkan, lalu ditinggal begitu saja di pelabuhan.
“Kami khawatir anak-anak PKL ini dipermainkan dan terjebak ‘calo’ yang bisa diduga melakukan praktik perdagangan. Yang pasti, mereka terperosok dalam praktik eksploitasi dalam pekerjaan,” lanjut Laode.
Syamsul Huda atau Yuda dari CV Bintang Cahaya Samudra di Jawa Tengah, perusahaan penyalur tenaga kerja, mengatakan adanya kerja sama dengan sekolah melalui perjanjian yang disepakati kedua belah pihak. Mereka bersepakat sesuai peraturan dan pedoman program PKL.
Namun, belakangan ia lebih selektif memilih SMK. Karena beberapa kali menjalankan kerja sama program PKL di Jawa Tengah, mereka mendapati anak PKL SMK yang baru sebulan melaut di kapal penangkap cumi sudah mengeluh tidak tahan dan ingin pulang.
Menurutnya, keinginan anak PKL yang sudah melaut lalu minta pulang di tengah perjalanan menyusahkan dan merepotkan. “Kami repot karena harus memulangkan mereka dengan jemputan melalui kapal kolekting. Maka, ya, kami mulai selektif membuka kerja sama dengan sekolah. Kami ingin memastikan anak-anaknya tangguh dan tidak sedikit-sedikit minta pulang karena tidak tahan di atas kapal. Repot kalau seperti itu,” katanya.
Jauh dari hak higenis
Selain persoalan dokumen dan kerasnya kehidupan di laut, ada pula pengalaman mereka yang tidak bisa diabaikan: hak kesehatan di atas kapal sebagai manusia. Bahkan itu termasuk hak anak, karena ada siswa PKL SMK berusia 16 tahun yang tetap melaut.
Salah satu contoh menyangkut fasilitas kamar mandi di kapal penangkap cumi atau kapal kolekting. Jawabannya: tentu saja tidak ada, jika yang dibayangkan adalah kamar mandi layak dengan pintu tertutup.
Jauh dari bayangan umum—tidak ada ruang dengan toilet jongkok atau duduk, tidak ada ember dan gayung, juga tidak ada keran air tawar bersih. Semua itu tidak tersedia.
“Kalau mau buang air besar (BAB), ya… ada lubang begitu saja. Airnya, ya, air laut. Awalnya canggung, gatal-gatal juga. Tetapi lama-lama dimaklumi saja dan diterima apa adanya,” cerita Arya.
Air laut dialirkan melalui selang yang terhubung dengan mesin tertentu, selama mesin kapal menyala. Jika mesin kapal mati, aliran air laut otomatis terhenti.
Kapal-kapal tersebut memang membawa air tawar dalam tandon di dalam kapal, namun hanya untuk kebutuhan memasak air matang dan makanan. Tidak boleh dipakai untuk kebutuhan lain.
Verdi (24) juga bercerita, saat ia ikut kapal penangkap cumi di usia 16 tahun, kapal yang ditumpanginya kehabisan bekal air tawar hingga juga kehabisan bahan makanan. Terpaksa mereka minum air laut sambil menunggu ada kapal lain yang berdekatan untuk meminta bantuan bahan makanan.
Atau mereka harus menunggu kapal kolekting yang datang membawa perbekalan, dipesan melalui jaringan Starlink oleh nahkoda atau ketua kapal.

Sumber : Unicef.
“Ya, jalani saja. Di tengah laut mau pergi ke mana? Hanya bisa berdoa kepada Tuhan, semoga selamat dan bisa kembali ke daratan dengan selamat. Mendapat bayaran, itu saja yang saya pikirkan. Kalau memikirkan bahaya, ya, semua berbahaya. Kalau memikirkan sehat, mana ada sehat di atas kapal. Dapur seadanya, bersebelahan dengan lubang buang air,” cerita Verdi.
Ketua Komisi Perempuan dan Anak Daerah (KPAD) Bali, Yastini, tak habis pikir ada anak PKL SMK kelautan yang dibiarkan “bekerja” di atas kapal jauh dari pengawasan sekolah, mengerjakan pekerjaan ABK, jauh dari sehat baik fisik maupun nonfisik. Hal ini menjadi perhatiannya dari kasus sembilan anak program PKL SMK dari luar Bali pada akhir Juni 2025, yang didaftarkan dokumennya sebagai ABK, bukan PKL SMK.
“Benar-benar ini ranah rawan eksploitasi. Kami khawatir bisa menjadi praktik perdagangan orang jika tidak terawasi dengan baik oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan,” katanya.
Ia berjanji lembaganya akan mengkaji program PKL SMK ini, terutama kebijakan dan peraturannya. Apalagi Pelabuhan Benoa, Bali, menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program PKL SMK, terutama dari berbagai daerah di luar Bali.
“Hal ini menjadi atensi kami… apalagi anak PKL ini ada yang mulai berusia 16 tahun dan masih termasuk anak-anak. Dinas pendidikan di masing-masing provinsi yang memiliki program PKL SMK kelautan seharusnya memberi perhatian lebih soal ini,” kata Yastini.
Liputan dan tulisan ini didukung oleh program pelatihan dan beasiswa kelautan dari Environmental Justice Foundation (EJF) dan Project Multatuli (PM).
Foto cover : Freepik